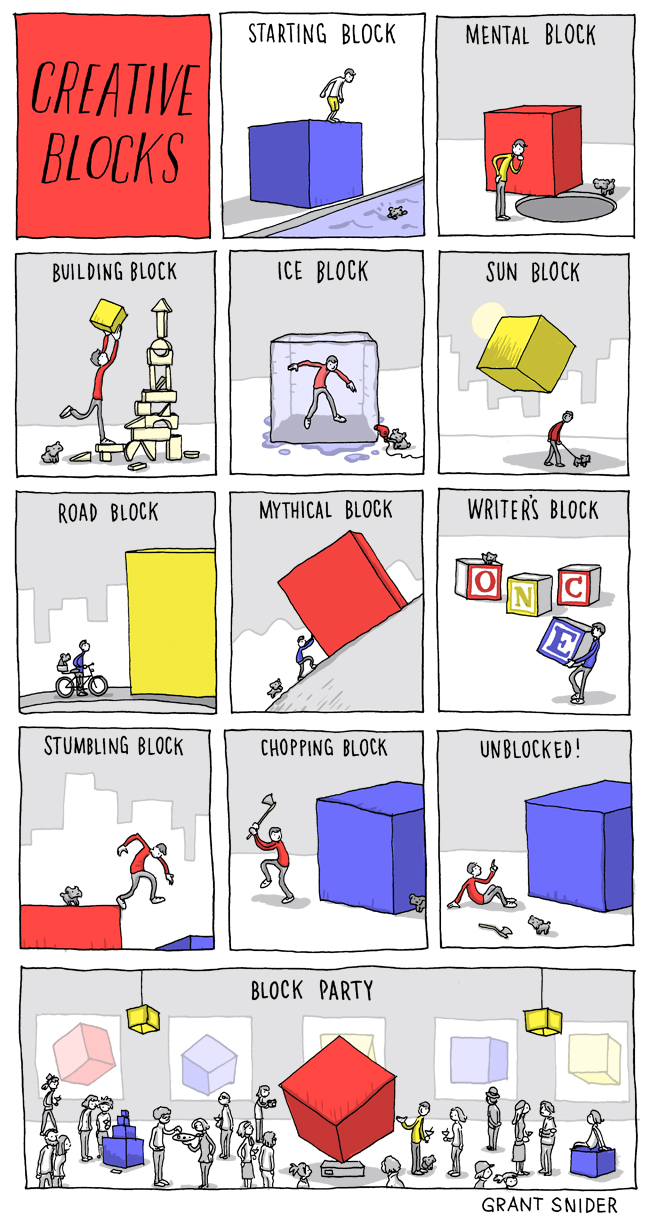Oleh : Mathori A Elwa. Penyair. Editor Senior Nuansa Cendekia, Tinggal di Jogjakarta.
Mereka, para sastrawan, penulis, jurnalis, dan kaum cerdik-cendekia–
tentu saja yang telah memiliki level kesadaran intelektual tinggi–
menyadari pentingnya kesusastraan sebagai nafas hidup mereka. Sebagian
karena alasan praktis, sebagian karena alasan yang abstrak.
Alasan praktis biasanya merujuk pada pentingnya merawat dan
mengembangkan imajinasi dalam diri manusia. Imajinasi dalam pengertian
ini adalah sebuah basis kreatif alam-pikir individu yang harus dirawat
dan dikembangkan, karena dengan itulah kreativitas itulah hidup akan
senantiasa berkembang.
Imajinasi juga dianggap penting mengingat manusia hidup tidak cukup
hanya menggunakan rasio murni, atau menurut Imanuel Kant, tak cukup
dengan mengandalkan “nalar instrumental”. Dengan sastra (dalam hal ini
fiksi), diharapkan pula dari sini muncul kecerdasan yang harmonis antara
otak kanan dan otak kiri.
Lain daripada itu, fiksi,–terutama karya-karya bermutu–, tidak
mengajak manusia terjebak pada tahayul. Dengan itulah mengapa sastra
diperlukan manusia modern, karena ia tetap memenuhi syarat untuk hidup
dalam ruang rasionalitas modern, tetapi menjebak pola-pikit ke dalam
“rasio-instrumental”, yang kaku, melainkan mengembangkan nalar secara
kreatif, dinamis dan bahkan mengajak kita hidup lebih humanis.
Argumen mendasar di atas itu kemudian menyadarkan kaum cerdik
cendekia senantiasa menggemari susastra dari beragam jenis. Tak jarang,
kegemaran mereka membaca susastra sangat gila. Kecanduannya dari remaja
hingga menjelang masuk liang kubur meliputi bacaan jenis puisi, novel,
hingga studi susastra ilmiah.
Namun, harus pula diakui bahwa dari penggila susastra itu hanya
menyadari/merasakan manfaatnya, tetapi sering tidak mampu menjelaskan
alasan mengapa ia gemar gila susastra. Rata-rata mereka hanya mampu
menjawab sebagai hobi. Tetapi alasan sebagai sekadar hobi sekalipun,
tetaplah baik. Sebab rata-rata penghobi susastra kebanyakan adalah
golongan orang-orang yang memiliki jiwa intelektualitas tinggi.
Keluarga bermutu peduli susastra
Sedikit alasan di atas, paling tidak akan membuka kesadaran kita
mengapa susastra tetap hidup di masyarakat modern, bahkan semakin maju
kebudayaan masyarakat, semakin banyak pecinta susastranya. Negara
Inggris, Jepang, Korea Selatan, Belanda, Amerika Serikat, Perancis,
Italia, dan beberapa negara maju lainnya telah membuktikan sebagai
bangsa dengan masyarakat penggila sastra yang luar biasa.
Dengan kata lain, saya ingin memastikan bahwa susastra memang
menempati golongan masyarakat “elit”, dalam artian elit secara
intelektual, atau elit secara adab, dan bukan semata elit secara
ekonomi. Sebab, harus diakui, tidak setiap orang kaya, bahkan mereka
yang elit dari sisi sosial seperti ningrat atau menak, menggilai
susastra.
Orangtua perlu sastra agar pikiran memiliki ruh, dan yang lebih
penting lagi adalah mampu menyelami dunia batin imajinasi. Ini sangat
penting karena kebanyakan anak-anak kita sangat lekat hidup dengan dunia
imajinasi yang penuh kreativitas.
Dengan menetapkan sastra sebagai bagian dari keluarga, kelak
anak-anak kita ketika dewasa akan hidup dengan jiwa dan karakter yang
lebih baik. Orangtua,–yang sekalipun selama masa mudanya, bahkan sampai
tua kurang menyukai dunia susastra,– tentu perlu mengubah pandangannya
tentang susastra yang tidak penting menjadi susastra itu maha penting.
Seandainya, tetap merasa tidak suka membaca, paling tidak harus memiliki
kepedulian untuk menanamkan pentingnya susastra bagi anak-anaknya.
Tentu bukan sekadar anjuran, melainkan mengajak anak-anak membaca, dan
orantua bijak selalu membelanjakan buku-buku susastra kepada
anak-anaknya.
Tema-tema susastra tidak terlalu sulit dipetakan. Ada fiksi seperti
novel dan cerpen, termasuk komik, ada pula karya puisi atau bentuk
cerita lainnya. Cerita-cerita rakyat, legenda, kisah hikmah, atau roman
sebanyak mungkin diberikan kepada anak-anak remaja. Perpustakaan sekolah
sejauh ini kurang memenuhi kebutuhan bacaan tersebut, karena itulah
orangtua harus mengalokasikan belanja buku-buku penting tersebut sebagai
bacaan remaja.
Pada level dewasa, selevel usia SMA dan mahasiswa, novel-novel karya
penulis-penulis besar dunia harus mulai dibaca. Bacaan sastra bermutu
karya Leo Tolstoy, H.G. Well, Najib Mahfudz, Rudyat Kipling, William
Shakespeare, Rabindranat Tagore, Dostoevky, John Galwrthy, Edgar Allan
Poe, Jalaluddin Rumi, Muhammad Iqbal, Kahlil Gibran, Najib Kaelani, Marx
Twain, Albert Camus, setidaknya disediakan di perpustakaan keluarga.
Begitu juga karya terbaik sastrawan Indonesia seperti Idrus, Muchtar
Lubis, Aoh K Hadimadja, Pramudya Ananta Toer, Remy Sylado, Ali Audah,
Ramadhan KH, Iwan Simatupang, Putu Wijaya, Kuntowijoyo, Titis Basino,
Gerson Poyk, YB Mangunwijaya, Ajip Rosidi, Umar Kayam, Budhi Dharma, NH
Dini, Seno Gumira Adjidarma, AS Laksana, Hamzah Fansuri, Amir Hamzah,
Chairil Anwar, Sutardji Calzoum Bachri, Goenawan Muhamad, WS Rendra, A
Mustofa Bisri, D. Zawawi Imron, Acep Zamzam Noor, Joko Pinurbo, Dorothe
Rosa Herliany, Widji Thukul, Linda Christanty, sebaiknya sudah menjadi
koleksi para remaja kita. Karya-karya penulis Indonesia yang saya sebut
itu mungkin bukunya tidak best-seller seperti Laskar Pelanginya Andreas
Hirata atau Supernova-nya Dewi Lestari, tetapi kedudukan nilainya tentu
lebih tinggi di banding susastra popular.
Melawan televisi
Jika hobi mengoleksi karya susastra sudah menjadi kebiasaan, waktu
“luang” anak-anak remaja dalam lingkungan keluarga secara otomatis akan
lebih penting digunakan untuk membaca, bukan menonton televisi. Keluarga
yang tidak memiliki koleksi bacaan yang bagus, waktunya dihabiskan
untuk menonton televisi atau cilakanya sekarang banyak membaca berita
online yang buruk mutunya.
Penelitian menunjukkan bahwa tontonan televisi yang digemari
mayoritas keluarga kita pasti tidak mendidik. Bahkan kini mulai tumbuh
kesadaran di kalangan keluarga terdidik, di rumah mereka tidak lagi
menyediakan televisi, melainkan VCD, agar selera anak-anak mereka dapat
diarahkan secara positif. Terbukti, bahwa keluarga demikian pasti
menggemari tontonan dan bacaan bermutu, bukan tontonan dekaden dan
membodohkan.
Waktu remaja, Rabindranat Tagore biasa mendengarkan dengan khusuk
ayahnya mendendangkan syair-syair Jalaluddin Rumi di samping
Bagawatgita. Tak heran jika Tagore tumbuh sebagai seorang yang
berpandangan luas dan imajinasinya tumbuh amat subur. Kita mengenalnya
sebagai pujangga besar India. Tradisi membaca karya sastra dan kitab
suci secara bersamaan sebenarnya berlaku di dunia Timur, terutama di
kalangan keluarga kelas menengah. Pendiri Tempo Group, Goenawan
Mohammad sejak remaja banyak dipasok pengetahuan oleh ayahnya dengan
bacaan-bacaan berjimbun dan diarahkan untuk memahami susastra. Ada pula
tokoh Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Nurcholis Madjid yang terbukti
menjadi manusia berkualitas kelas internasional karena tradisi
keluarganya sangat kuat dengan literatur susastra.
Di Indonesia, terutama pada keluarga kaum santri sebenarnya sudah
punya potensi dengan dekatnya mereka dengan susastra Arab. Selain
membaca Kitab suci Al-Quran, keluarga santri juga menyertakan bacaan
susastra bermutu seperti susastra klasikAl-Barjanji, Maulid Diba’,
Simdud Durar dll. Bahkan ketika memiliki hajat, misalnya mau membangun
rumah, karya sastra yang bertajuk Manaqib Syeikh Abdul Qadir Jilani
dibaca dengan melalui prosedur tertentu, yakni membuat ingkung (memasak
ayam jantan) dan beberapa jenis makanan dan minuman tertentu; pemasaknya
orang yang sudah tidak bisa haid, ketika memasak tidak boleh berbicara
alias harus “topo bisu”, dan seterusnya).
Sementara di sebagian kalangan keluarga keturunan Cina, bacaan-bacaan
tentang susastra dan sejarah Tiongkok juga cukup menjadi tradisi yang
bisa diandalkan. Itu adalah modal besar bagi bangsa kita untuk
menghargai karya sastra secara kreatif.
Pembentukan karakter dimulai dari keluarga. Dan karya sastra bermutu
mengisi jiwa kita dengan asupan cahaya spiritualitas, seperti halnya
Kitab Suci mengisi jiwa kita dengan cahaya Ilahi. Keluarga tanpa asupan
kedua jenis spiritualitas demikian dapat dipastikan jiwanya kering
kerontang, karakternya rapuh, wataknya kaku dan keras, hatinya angkuh,
tak sudi belajar kepada orang lain, anti-kritik, dan —celakanya— senang
menyaksikan pembunuhan atau tayangan horor, –lebih celaka lagi– hobi
membunuh sesama manusia
Karena itu, jika kita sekarang sedang mendengar slogan “revolusi
mental” barangkali salahsatu agenda terpentingnya adalah menjadikan
setiap keluarga sebagai keluarga yang memiliki kesukaan terhadap karya
susastra bermutu.
Sebab, kalau sekedar banyak baca tetapi bacaannya adalah karya kurang
berkualitas, atau bahkan hanya sekadar baca informasi online yang
muatannya kebanyakan sampah, sulitlah kita berharap munculnya
manusia-manusia Indonesia yang berbudi pekerti sejalan dengan idealitas
pancasila .[]