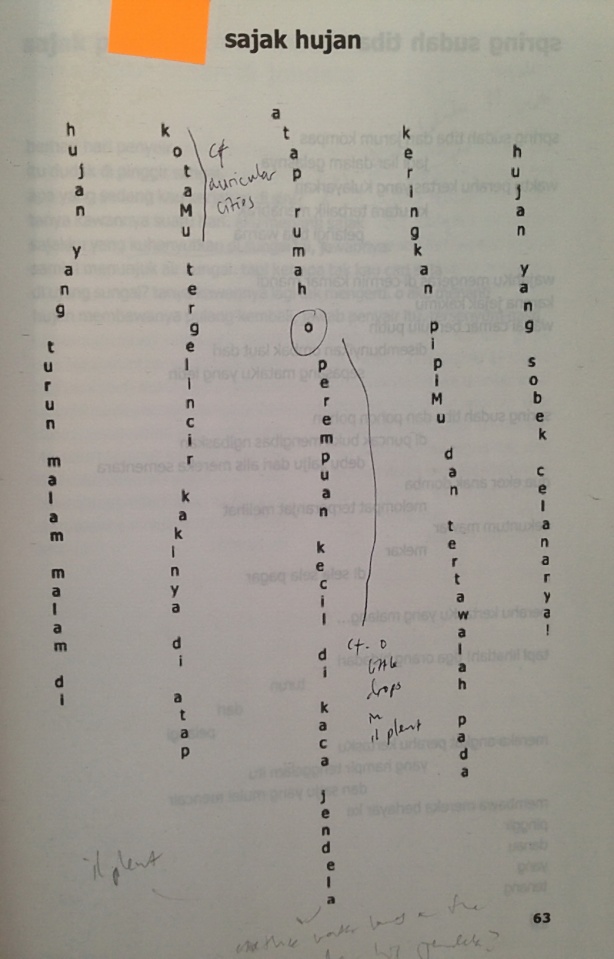oleh: Mikael Johani*

Aneh bahwa belum pernah ada review yang benar-benar membahas tentang
buku kumpulan puisi Saut Situmorang yang diterbitkan tahun 2007,
“otobiografi: kumpulan puisi 1987-2007″ (o-nya memang sengaja kecil),
selain
review almarhum Asep Sambodja yang juga pernah dibawakan dalam diskusi tentang buku ini di acara
Meja Budaya
asuhan Martin Aleida di PDS H.B. Jassin di TIM pada tahun 2009. Padahal
biasanya dalam dunia sastra Indonesia, figur yang seterkenal Saut akan
menarik banyak groupies sastra untuk menulis review tentang
buku-bukunya. Lihat saja ledakan review tentang buku-buku Ayu Utami
(pemenang pertama lomba esai DKJ yang terakhir pun masih membahas buku
dia!–walaupun dengan nada mengkritik), Nirwan Dewanto, dan Nukila Amal
(di tahun yang lain lagi, lomba esai DKJ yang sama dipenuhi begitu
banyak tulisan lebay-pretentious tentang novelnya yang dianggap super
rumit sehingga pasti nggak mungkin nggak adiluhung itu, Cala Ibi).
Pendek kata, hype dan kultus individu dalam sastra Indonesia biasanya
menghasilkan tulisan yang cukup banyak tentang individu tersebut (nggak
usah ngomong dulu tentang kualitasnya), tapi kenapa setelah tujuh tahun
belum ada lagi juga esai selain esai Asep yang membahas secara serius
puisi-puisi Saut dalam kumpulan seminalnya ini?
Jawaban singkatnya, karena Saut Situmorang tidak cuma terlahir dari
sejarah sastra Indonesia, tapi juga dari sejarah sastra, puisi, dan seni
di luar Indonesia, dari puisi Modernis ala Eliot, Surrealis ala Rimbaud
(kumpulan puisi Saut yang baru berjudul Perahu Mabuk = Le Bateau
ivre-nya Rimbaud), puisi-puisi kalligram ala Apollinaire, Négritude ala
Aimé Césaire, puisi protes ala Neruda, puisi Beat ala Ginsberg, haiku
ala Basho (via Pound?), gerakan meng long shi (Misty Poetry) Tiongkok,
dan itu baru pengaruh-pengaruhnya dari dunia puisi di luar Indonesia!
Saut juga banyak memamerkan pengaruh-pengaruhnya dari dari dunia film
(Tarkovsky, misalnya), dunia seni (Magritte dan Duchamp, misalnya), dan
pop culture (Speedy Gonzales, misalnya–walaupun ini bisa juga permainan
intertekstualitas dengan Ashbery!). Dan masalahnya, sori-sori aja,
kebanyakan kritikus sastra Indonesia tidak tahu sama sekali tentang
sejarah apalagi teori puisi di luar Indonesia. Sehingga sederhananya,
mereka nggak ngerti puisi-puisi Saut! Mereka nggak menangkap
alusi-alusinya, nggak bisa melacak kepadatan intertekstualitas (bukan
cuma name-dropping ala Nirwan Dewanto) dalam puisi-puisinya, nggak tahu
permainan dan perang apa yang dilancarkan Saut bukan cuma dalam
puisi-puisinya tapi juga dengan caranya menyusun puisi-puisi itu dalam
kumpulan ini.
Padahal, dalam kumpulan ini, Saut selain berpuisi juga sedang
melancarkan protes dan revisinya terhadap puisi Indonesia dan juga puisi
Barat berbahasa Inggris yang sepertinya masih berusaha melepaskan diri
dari bayang-bayang Puisi Modernis dan tanpa sadar sudah lebih dari
setengah abad muter-muter di situ aja. Saut (menulis dalam bahasa
Indonesia kecuali di bagian terakhir yang diberi subjudul “Rantau” dan
berisi puisi-puisi bahasa Inggrisnya) mencari jalan keluar dari anxiety
of influence yang ditinggalkan penyair-penyair Modernis (favorit Saut
sendiri sepertinya Eliot) dengan mengadopsi, mengapropriasi, me-mashup
pengaruh tersebut dengan tradisi-tradisi kepenyairan di luar gerakan
Modernis tersebut–dari surealisme Prancis, writing back ala Négritude,
blues ballad ala Rendra (via Lorca?), sampai sajak terang sadar politik
penyair-penyair Indonesia tahun 1990an (misalnya puisi protes Wiji
Thukul). Yang dihasilkan oleh kumpulan puisi otobiografi ini adalah
sesuatu yang revolusioner: sebuah dialog (atau mungkin struggle?) dengan
(anxiety of) influences Saut sendiri, sebuah usaha untuk menaklukkan
mereka dengan pendekatan yang postmodern: multi-tradisi,
multi-intertekstual, bahkan multi-bahasa!
A. Tradisi versus bakat individu
otobiografi diawali dengan sebuah esai dari Saut yang berjudul “
Tradisi dan Bakat Individu“.
Judul esai ini adalah terjemahan langsung dari esai terkenal T.S.
Eliot, Tradition and the Individual Talent. Esai ini bertindak sebagai
manifesto kesenian Saut. Seperti Eliot, ia berpendapat tidak mungkin
seorang penyair atau sastrawan, seberbakat apapun, berkarya tanpa
dipengaruhi tradisi-tradisi yang mendahuluinya. Justru cara si sastrawan
bergulat dengan tradisi-tradisi yang mempengaruhinya itulah yang
menarik! Saut dengan eksplisit menyatakan tidak setuju dengan
pernyataan-pernyataan lebay-asersif kritikus-kritikus Indonesia dari
sejak H.B. Jassin sampai Nirwan Dewanto yang sering tanpa bukti jelas
mengklaim bahwa seorang pengarang yang berbeda sedikit saja dari
teman-teman seangkatannya pasti tidak terlahir dari sejarah sastra
Indonesia(nya) sendiri. Dari Chairil yang terlalu sering diklaim sebagai
binatang jalang yang dari kumpulan masteng sastra 45-nya terbuang,
sampai Ayu Utami dan Saman yang diklaim oleh temannya Nirwan Dewanto
tidak terlahir dari sejarah sastra Indonesia–sampai-sampai blurbs buku
itu pun dengan enteng sengaja salah mengutip komentar Pramoedya Ananta
Toer, seakan-akan ia terlalu kuno dan nggak ngerti Saman! Soal Chairil,
Saut menunjukkan bahwa pada tahun 1992, peneliti sastra Indonesia Sylvia
Tiwon sudah pernah menganalisa relasi intertekstual antara puisi
Chairil dan pendahulu Pujangga Barunya, Amir Hamzah. By the way, Nirwan
Dewanto mengklaim hal yang sama dalam esainya tentang Chairil Anwar, “
Situasi Chairil Anwar“,
yang kemudian dimuat menjadi kata pengantar di kumpulan puisi Chairil
Anwar terbaru terbitan Gramedia tahun lalu. Selain esai ini Nirwan ini
telat, madingnya udah terbit, ia juga tidak sekalipun menyebutkan bahwa
poin yang dibuatnya sudah pernah dibuat pula oleh Sylvia Tiwon (apalagi
Saut Situmorang!), mungkin karena ia memang nggak tahu tentang esai
terkenal Sylvia Tiwon itu, atau dia pengen orang-orang menganggap dia
sendiri yang muncul dengan pikiran itu. Seakan-akan dia sendiri tidak
terlahir dari sejarah kritik sastra Indonesia! Hahahahaha!
Patut diperhatikan pula bahwa esai Tradisi dan Bakat Individu ini
juga diterbitkan dalam kumpulan esai Saut Situmorang, Politik Sastra,
yang terbit dua tahun kemudian, 2009. Kumpulan kritik sastra ini, selain
sebuah j’accuse! terhadap kebusukan politik sastra Indonesia, juga bisa
dibaca sebagai manifesto kepuisian Saut versi extended. Jika kamu ingin
lebih mengerti puisi-puisi Saut, bacalah Politik Sastra, di situ ia
layaknya sebuah buku panduan membaca simbolisme lukisan Old Masters,
menyebar clues tentang pengaruh-pengaruh dalam puisinya dan bagaimana ia
mengolah pengaruh-pengaruh tersebut. Misalnya, jika ingin clues tentang
bagian pertama otobiografi, “Cinta”, bacalah esai “Dikutuk-sumpahi
Eros” dalam Politik Sastra. Jika ingin lebih mengerti bagian terakhir
otobiografi, “Rantau”, baca “Sastra Eksil, Sastra Rantau” dalam Politik
Sastra. Menarik pula untuk diingat bahwa eksistensi Saut sebagai
poet-critic/shit-stirrer dalam dunia kang ouw sastra Indonesia bisa juga
dianggap sebagai usaha mewarisi tradisi penyair-penyair Modernis yang
sering juga punya identitas ganda sebagai kritikus pengguncang status
quo. Dalam hal ini (bagian critic dari poet-critic), mungkin Saut
sebenarnya lebih mirip dengan Ezra Pound daripada Eliot, lebih
shit-stirring dan lebih subversif. Jika kamu, seperti Goenawan Mohamad,
menganggap jurnal boemipoetra yang ia terbitkan hanya sekedar “
coret-coret di kakus“, coba deh download kopian zine
Blast
yang dieditori Ezra Pound di awal abad 20. boemipoetra itu, seperti
hampir semua yang dilakukan Saut Situmorang, bukan sekedar coret-coret
di kakus, tapi coret-coret di kakus yang hiperintelektual dan
hiperintertekstual! Sampai GM aja nggak ngerti! Kakus boemipoetra itu
dilengkapi urinal ready made Duchamp, lho! Hahahahaha!
Setelah esai Tradisi dan Bakat Individu, menyusul bagian pertama
otobiografi, “Cinta”. Di sinilah Saut bergulat dengan sumber anxiety of
influencenya yang pertama dan mungkin paling utama: Chairil Anwar. Bukan
sok-sokan jika bagian ini dimulai dengan kutipan terkenal dari puisi
“Tak Sepadan” Chairil: “Dikutuk-sumpahi Eros, aku merangkaki dinding
buta, tak satu juga pintu terbuka.” Jika Chairil berusaha mencari pintu
keluar dari kutuk-sumpah Eros, Saut berusaha di bagian ini untuk mencari
pintu terbuka yang menawarkan jalan keluar dari pengaruh Chairil!
Bagaimana cara Saut melakukan itu? Dengan mengerahkan semua arsenal
pengaruh-pengaruhnya yang lain! Dari kaligram ala Apollinaire
(bandingkan bentuk puisi “dongeng enggang matahari”

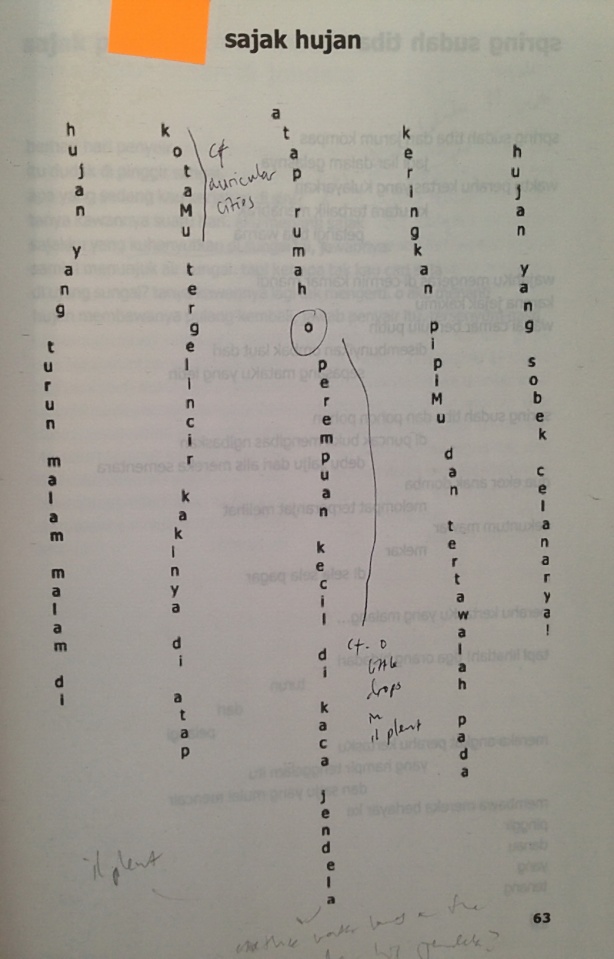
dengan “
Il Pleut”
(by the way, baris “hujan… tergelincir kakinya di atap atap rumah”
dalam “sajak hujan” juga diapropriasi kemudian direkontekstualisasi dari
baris “la pluie qui met ses pieds dans le plat sur les toits” dalam
puisi Aimé Cesaire “Le Cristal automatique”), puisi imagis ala William
Carlos Williams dengan variable foot dan barisnya yang pendek-pendek
(bandingkan puisi “elegi claudie” dengan “
The Red Wheelbarrow”),
haiku modernis ala Pound via Sitor (bandingkan “lonceng gereja, tembok
kota tertawa padanya” dengan “In a Station of the Metro, the apparition
of these faces in the crowd, petals on a wet, black bough” dengan “Malam
Lebaran, bulan di atas kuburan”), mash-up puisi Zen-Beat ala Ginsberg
dengan plesetan kutipan dari Eliot (puisi “kata dalam telinga”, baris
“Jumat adalah hari yang paling kejam dalam seminggu” yang memelesetkan
baris terkenal dari “The Waste Land”, “April is the cruellest month,
breeding lilacs out of the dead land”), sampai Sapardi Djoko Damono!
(lihat puisi “Aku mencintaiMu dengan seluruh jembutKu”.)
Dan masih banyak lagi. Poin semua ini adalah, satu, seperti argumen
Bloom di buku terkenalnya “The Anxiety of Influence: A Theory of Poetry”
yang juga dikutip oleh Saut dalam esai Tradisi dan Bakat Individu di
awal otobiografi ini, mendistorsi karya-karya/gaya-gaya
penyair-penyair/tradisi-tradisi kepenyairan yang mendahului dan
mempengaruhinya tadi menjadi karya/gaya/tradisi-nya sendiri, dan dua,
seperti seorang guru yang menerapkan mantra “show, don’t tell”
Hemingway, menunjukkan hutang penyair-penyair Indonesia yang dianggap
pendobrak tradisi seperti Chairil, Sitor, dan Sutardji terhadap
tradisi-tradisi puisi Barat yang dengan sengaja mereka apropriasi (puisi
Modernis buat Chairil dan Sitor, kalligram ala Apollinaire dan Puisi
Konkrit buat Sutardji).
Tentu, Saut secara sengaja juga menunjukkan betapa berhutangnya dia
kepada tradisi dan sejarah puisi yang mendahuluinya. Puisi-puisi ini
adalah pembuktian manifesto Bakat dan Tradisi Individunya tadi, caranya
(memelesetkan kalimat terakhir di esai itu) menunjukkan bagaimana dia
menjadi bagian dari tradisi/sejarah sastra Indonesia, sekaligus
menunjukkan relasi intertekstual puisi-puisinya dengan puisi-puisi
sebelumnya.
Bagian kedua otobiografi dijuduli “Politik”. Di sinilah Saut
menunjukkan bahwa salah satu bagian dari identitas kepenyairannya adalah
keanggotaan tidak resminya dalam “angkatan” penyair Indonesia 1990an.
Seperti dikatakannya di esai Bakat dan Tradisi Individu: “Sebuah motif
dominan lain pada puisi para penyair 1990an adalah politik. Para penyair
1990an tidak lagi tabu atau malu-malu untuk mempuisikan politik,
mempolitikkan puisi, malah justru pada periode inilah puisi politik
mencapai puncak ekspresi artistiknya yang melampaui apa yang sebelumnya
dikenal sebagai sajak-protes dan pamflet-penyair seperti pada puisi Wiji
Thukul.”
Strategi puitis yang dipakai Saut di bagian “Politik” ini sama dengan
yang dipakainya di bagian “Cinta”: lebih banyak lagi distorsi dan
revisi atas pengaruh-pengaruh tradisi yang mendahuluinya. Puisi pertama
dalam bagian ini saja berjudul “potret sang anak muda sebagai penyair
protes”, judul alusif yang sekaligus memelesetkan frase terkenal dari
pentolan (prosa) besar Modernis Joyce dan pentolan Komunitas Utan
Kayu/Salihara Goenawan Mohamad yang lebih dulu memelesetkan frase itu
(“A Portrait of the Artist as a Young Man” → “Potrét Seorang Penyair
Muda Sebagai Si Malin Kundang”).
Salah satu puisi yang paling menarik dalam bagian “Politik” ini
adalah puisi “demikianlah”. Dalam puisi ini, Saut menggabungkan
berbicara tanpa malu-malu tentang politik (“langit yang biru lebam
dihajar popor m-16 anjing anjing kapitalis pascakolonial) dengan
irama-irama puisi Beat ala Ginsberg dan obsesinya dengan budaya pop dan
obscenity (“demi dr strangelove yang berkhayal nikmatnya sebuah rudal
yang pecah di lobang duburnya”) dan semacam katalog influences atas
kepenyairannya (Harry Roesli, Alfred Hitchcock, Rendra, Wiji Thukul,
Karl Marx, Guernica Picasso, Made Wianta, lagu anak-anak Pelangi,
Tampax, SMS, Borobudur, Bukek Siansu, National Geographic, dan masih
banyak lagi).
Bagian “Politik” ini juga jadi cara efektif buat menghapus stigma
hangover Orba bahwa sajak yang bertema politik seperti puisi pamflet
Rendra atau sajak protes Wiji Thukul pasti kurang “puitis” atau malah
kurang “adiluhung”. Saut membuktikan dengan sajak-sajaknya di bagian ini
bahwa “sajak politik” tidaklah serta-merta (hanya karena subject
matternya) sederhana, naif, dan primitif seperti yang sering dituduhkan
oleh penyair-kritikus salon Salihara, tapi juga bisa canggih,
intertekstual, dan postmodern. Stigma bahwa sajak politik pasti jelek
hanyalah hangover (anxiety of influence!) Orba, bagian dari
propagandanya untuk men-depolitisasi seni di Indonesia.
B. Writing back to the canon
Bagian ketiga otobiografi berjudul “Rantau”, berisi puisi-puisi
bahasa Inggris Saut. Di sinilah Saut takes the game to his influences
head on! Di bagian inilah usaha Saut untuk keluar dari bayang-bayang
Puisi Modernis paling kelihatan. Yang ia lakukan dalam bagian ini adalah
semacam tour de force melewati berbagai macam genre dan subgenre puisi
Barat dan Indonesia yang menawarkan obat penawar untuk hangover Puisi
Modernis, yang dalam dunia puisi Barat berbahasa Inggris pun sepertinya
belum ditemukan. Kebanyakan penyair berbahasa Inggris masih terjebak
dalam curhatan borjuis confessional poetry ala Lowell, Plath, dkk, atau
permainan borjuis-esoterik
flarf,
dan keduanya tidak relevan dengan kondisi pascakolonial (penyair)
Indonesia (atau penyair yang lahir dari sejarah sastra Indonesia seperti
Saut). “Rantau” menunjukkan salah satu episode paling penting dari
otobiografi kepenyairan Saut, saat dia menulis puisi sebagai usaha
“writing back” kepada otoritas kanon Puisi Barat yang mempengaruhinya.
Tidak heran apabila bagian ini dimulai dengan kutipan favorit para
pascakolonialis dari drama Shakespeare, The Tempest: “You taught me
language, and my profit on’t is I knew how to curse.” Kutipan ini salah
satu baris yang diucapkan oleh Caliban, antagonis utama dalam The
Tempest, tapi justru protagonis dan poster boy pemikir pascakolonial,
termasuk salah satu idola Saut, Aimé Cesaire, yang mengangkat Caliban
sebagai seorang black slave-hero yang melawan white masternya Prospero
dalam adaptasinya atas The Tempeste, Une Tempête. Patut diingat bahwa
dalam salah satu baris yang mengikuti baris yang dikutip Saut di atas,
Caliban mengutuk Prospero dan Miranda yang mengajarinya bahasa Inggris,
semoga “the red plague rid you for teaching me your language!” Namun,
yang dilakukan Caliban-Saut dalam bagian “Rantau” ini, seperti juga yang
sebenarnya dilakukannya di balik sumpah-serapah j’accuse!-nya di
Twitter dan Facebook tapi tidak banyak disadari orang, bukan cuma
cursing tapi sebuah proses writing back terhadap kanon puisi Inggris!
Dalam puisi “Looking for Charles Bukowski in K Rd” misalnya, Saut
mendistorsi waste land urban Eropa pra- dan pasca-Perang Dunia I yang
digambarkan Eliot dalam dua puisi yang dianggap memelopori Puisi
Modernis, “The Love Song of J. Alfred Prufrock” (“half-deserted streets,
… restless nights in one-night cheap hotels”) dan “The Waste Land”,
menjadi waste land “retro paradise” “red-light-cum-nightclub-district” K
Rd di Auckland, metropolis terbesar di New Zealand. Dalam puisi ini,
Saut kembali memelesetkan “April is the cruellest month” Eliot dari “The
Waste Land” menjadi “Friday is the holiest night of the week”
(ironically, of course), me-mashup-nya (lagi) dengan irama Beat dan
obscenity ala Ginsberg (“shit & death”, “prophets of semen
redemption”, “perfumed communion of alcohol & semen”), dengan
referensi budaya pop dalam bentuk kutipan lagu The Beatles (“obladi
oblada life goes on, yeah…”), kemudian mengakhirinya dengan memelesetkan
tiga baris pembuka “The Love Song of J. Alfred Prufrock” yang sangat
terkenal (yang judulnya juga dia pelesetkan jadi judul satu lagi
puisinya, yang rasanya bukan kebetulan ditaruh pas setelah puisi
“Looking for Charles Bukowski in K Rd” ini, “Love Song of Saut Speedy
Gonzales”): “Let us go then, you and I, when the evening is spread out
against the sky, like a patient etherised upon a table”, menjadi “let us
go to K Rd then, you & I, while the evening is still spread out
against the Sky Tower, like a Holy Virgin intoxicated upon a bar table”.
Yang paling mencengangkan sekaligus mengacengkan di sini adalah
distorsi simile Eliot yang dingin dan mencekam, “like a patient
etherised upon a table” menjadi simile yang hot dan mencekam, dan
sacrilegous (!), “like a Holy Virgin intoxicated upon a bar table.”
Sungguh sebuah distorsi yang sangat pas untuk mengubah baris-baris Eliot
yang menggambarkan urban Eropa yang sepi dan membusuk (ingat
“half-deserted streets”) menjadi baris-baris Saut yang menggambarkan
waste land K Rd yang ramai dan busuk!
Sementara itu, puisi selanjutnya, “Love Song of Saut Speedy
Gonzales”, sudah intertekstual sejak judulnya. Judul ini bisa dibaca
sebagai mash-up antara “The Love Song of J. Alfred Prufrock” dengan nama
karakter kartun Looney Tunes
Speedy Gonzales, tikus tercepat di Meksiko, atau dengan nama karakter kartun ini
setelah digunakan oleh John Ashbery dalam puisinya “
Daffy Duck in Hollywood”.
Bentuk puisinya sendiri adalah sebuah contoh “definition poem” yang
Oulipoesque, usaha Saut Speedy Gonzalez untuk mendefinisikan “love”
seperti entry sebuah dictionary. Love di sini didefinisikan dan
redefinisikan berkali-kali dengan berbagai macam metafora, referensi,
dan alusi. Salah satu yang khas Saut, surreal, liris, pop, sekaligus
obscene, adalah “love is the tampon that you mistook for a Chinese
herbal tea-bag”.
Dalam bagian “Rantau” ini, Saut memakai bahasa Inggris yang ia serap
selama masa perantauannya sebagai senjata (the pen is mightier than the
sword!), bukan untuk melenyapkan anxiety of influencenya yang berasal
dari kanon puisi dunia, tapi untuk berdamai dengan influence(s)
tersebut. Selain nama-nama yang sudah disebut di atas, influences itu
juga termasuk Baudelaire (dalam “after Baudelaire”), Rendra (“After
Rendra 3”), Li Po (“homage to Li Po”), Andrei Tarkovsky (“to Andrei
Tarkovsky”), René Magritte (“totem–to René Magritte”), Jimi Hendrix
(“1966–for Jimi Hendrix”), dan masih banyak lagi.
Dengan referensinya ke penyair non-Inggris (Baudelaire, Li Po,
Rendra) dan non-penyair (Tarkovsky, Magritte, Hendrix), Saut seperti
ingin menunjukkan kepada puisi bahasa Inggris bahwa jalan keluar dari
Puisi Modernis bisa saja berasal dari puisi yang tidak berbahasa Inggris
atau bahkan bukan dari dunia puisi!
Namun usul Saut ini pun mungkin tidak sepenuhnya orisinil, karena
Ezra Pound, malaikat penolong/Ibu Theresa penyair-penyair Modernis itu,
juga pernah mengusulkan hal yang sama dalam kanto-kantonya: menca/uri
jalan ke depan setelah Puisi Modern dari Confucius, Dante, Homer,
Gaudier-Brzeska, ilmu ekonomi, dan masih banyak lagi. Yang berbeda dari
Saut adalah identitas, otobiografi kepenyairannya. Ia menyerang kanon
puisi berbahasa Inggris sebagai Caliban, writing back dari dunia ketiga
ke pusat empire, sementara Pound, yang sering tidak benar-benar bisa
membaca sumber-sumber non-Inggrisnya, menyerang sebagai Prospero,
sebagai white master dari pusat empire itu sendiri.
Kesadaran Saut akan posisinya yang khas subyek pascakolonial itu
menjadikannya unik di dalam dunia kang ouw sastra Indonesia. Karena
alih-alih sadar akan posisi diri mereka yang lahir dari sejarah sastra
Indonesia yang always already pascakolonial dan karena itu perlu untuk
mempertanyakan, mengkritik, kemudian merevisi pengaruh-pengaruh mereka
yang berasal dari kanon sastra Barat, mereka justru mem-fetish-kan
pengaruh-pengaruh Barat itu dan menjadi sekelompok penyair inlander yang
tidak pernah bisa berdamai dengan, apalagi melampaui!, anxiety of
influencenya.
C. Intertekstualitas versus name-dropping
Kalau kritikus sastra Indonesia bicara tentang intertekstualitas saat
ini, mereka biasanya akan menyebut nama Nirwan Dewanto sebagai contoh
seorang penyair Indonesia kontemporer yang “intertekstual”. Biasanya ini
disebabkan karena
klaim
Nirwan sendiri, atau fakta bahwa ia sering mendedikasikan
puisi-puisinya buat penyair/seniman/musisi asing yang jarang terdengar
namanya sehingga rasanya o so hipster sekali, atau kalau tidak begitu
menyitir baris-baris puisi mereka dalam puisinya sendiri. Tapi bagaimana
dan untuk apa Nirwan menyebutkan nama mereka dan menyitir puisi-puisi
mereka? Apakah sekedar menyebutkan nama dan atau mengutip baris puisi
orang lain cukup untuk menghasilkan puisi yang intertekstual?
Mari kita bahas salah satu puisi Nirwan yang melakukan keduanya,
sebuah puisi berjudul “Burung Merak” dari “himpunan” (o so pretentious!)
puisinya, “Jantung Lebah Ratu”. Puisi “Burung Merak” ini didedikasikan
“untuk Juan José Arreola dan Wallace Stevens”. Wallace Stevens, satu
lagi punggawa Puisi Modernis, pernah menulis sebuah puisi berjudul
“Anecdote of the Prince of Peacocks”, yang (sepertinya, you’re never
sure with Stevens) bercerita secara imagis tentang dunia penyair
(“Prince of Peacocks”) yang menakutkan (“I met
Berserk”).
Puisi Nirwan “Burung Merak” (hampir pasti, karena hampir semua puisi
Nirwan selalu tentang betapa menyiksanya menjadi seorang penyair) juga
tentang dunia penyair yang menakutkan. Dalam “Burung Merak”, penyair
diumpamakan sebagai “pemburu”: “Ia sering mengaku tahu rahasia semua
jalan yang dilalui para pemburu. Sebenarnya mereka adalah kaum
penyair…”. Paragraf (puisi ini berbentuk puisi prosa, seperti layaknya
sebuah puisi Nirwan Dewanto) yang mengutip Stevens langsung berbunyi
begini: “Tetap saja ia merasa lebih tinggi ketimbang segala pohon dan
lebih luas ketimbang hutan sebab ia mampu menjangkau matahari dengan
matanya dan laut dengan telinganya. (Aku berhutang ungkapan ini kepada
seorang penyair dari negeri putih, pegandrung burunghitam, yang hampir
saja menjebaknya di pinggir hutan. Sejak itu aku tahu bahwa pena lebih
tajam ketimbang pedang. Ah, sungguh harfiah, bukan?)” Sekarang
bandingkan dengan “ungkapan” aslinya: (stanza ketiga dari “Six
Significant Landscapes”) “I measure myself against a tall tree. I find
that I am much taller, for I reach right up to the sun, with my eye; and
I reach to the shore of the sea with my ear.” Selain itu, “burunghitam”
berasal dari salah satu puisi Stevens yang paling terkenal “Thirteen
Ways of Looking at a Blackbird” (perhatikan cara penulisan “burunghitam”
yang disambung dan tak wajar dan berhutang banyak pastinya kepada cara
Stevens mengeja “Blackbird”), yang mise-en-scènenya “
Among twenty snowy mountains” di (sepertinya, you’re never sure with Stevens)
Haddam, Connecticut, 26,8 mil dari ibukota Connecticut, Hartford,
tempat Stevens menghabiskan kebanyakan masa hidupnya menulis puisi dan
bekerja di perusahaan asuransi. Dibandingkan dengan Hartford, Haddam di
tahun 1917 (tahun penerbitan “Thirteen Ways of Looking at a Blackbird”)
pasti memang terkesan seperti “pinggir hutan”! Sementara itu, “pena
lebih tajam ketimbang pedang” adalah terjemahan verbatim dari pemeo
Inggris “The pen is mightier than the sword”, yang pertama kali muncul
in print di naskah drama penulis Inggris Edward Bulwer-Lytton,
“Richelieu; Or the Conspiracy”.
Sekarang bandingkan cara “berhutang” Nirwan Dewanto kepada Stevens
dengan cara berhutang Saut kepada Eliot seperti dideskripsikan
sebelumnya. Betapa “sungguh harfiah”-nya memang cara Nirwan menyitir
Stevens! Bahkan sampai ke subject matter puisinya sendiri! Mana
distorsinya, mana revisinya, seperti yang dilakukan Saut?
Intertekstualitas, menurut Julia Kristeva yang meng-coin istilah ini,
selalu mengandung sebuah
transformasi. Mana transformasi teks Stevens dalam (kon)teks puisi Nirwan? Tidak ada!
Kemudian pertimbangkan kebenaran satu lagi pemeo terkenal dari Eliot
berikut ini: “immature poets imitate; mature poets steal; bad poets
deface what they take, and good poets make it into something better, or
at least something different.”
Mungkin menunjukkan bahwa “intertekstualitas” Nirwan Dewanto adalah
satu lagi kasus “The Emperor’s New Clothes” dari pujangga-pujangga
adiluhung kantong budaya Salihara bukan raison d’être utama Saut menulis
puisi-puisinya, karena intertekstualitas itu sendiri adalah salah satu
kondisi utama Modernisme, dan Saut sebagai penyair yang sangat
dipengaruhi oleh Modernisme dan terus-menerus bergulat dengan pengaruh
itu mungkin secara alami dan secara sadar (menggunakan bakat alam dan
intelektualismenya!) menggunakannya sebagai salah satu modus operandi
kepenyairannya. Namun, mengingat bahwa menunjukkan kenyataan kalau the
Salihara emperors have actually got no clothes on adalah salah satu
raison d’être politik sastra Saut selama ini, jangan didiskon dulu
kemungkinan bahwa Saut memang sengaja mengkurasi puisi-puisi yang
menonjolkan intertekstualitas yang sebenarnya dalam kumpulan otobiografi
ini–untuk mengekspos dusta hagiografi penyair-penyair sok intertekstual
dari KUK/Salihara!
“The only real emotion is anxiety”
Begitu kata satu lagi pentolan Modernisme, Freud. Kumpulan puisi
otobiografi ini pada akhirnya memang sebuah otobiografi kepenyairan Saut
Situmorang, kisahnya berjuang dengan anxiety of influence(s)nya, yang
membawanya merantau dari Puisi Modernis-Imagis ala Eliot kemudian
migrasi ke puisi Beat ala Ginsberg, puisi Négritude ala Cesaire, time
travel ke puisi-puisi surrealis Rimbaud, memulung found poetry, membetot
balada-balada blues ala Rendra, mengutuk-sumpahi Eros seperti Chairil,
mengutuk-sumpahi Orba seperti Wiji Thukul–dan along the way writing back
dengan penuh gusto (and not a little cursing!) dari prakondisi
pascakolonialnya, dengan jitu mengidentifikasi bahwa semua
pengaruh-pengaruh itu harus didistorsi, dikritisi, dan direvisi, kalau
ia memang ingin otobiografi kepenyairannya punya identitas sendiri.***
*Mikael Johani, penyair dan kritikus posmo, tinggal di Ciledug, Tangerang.